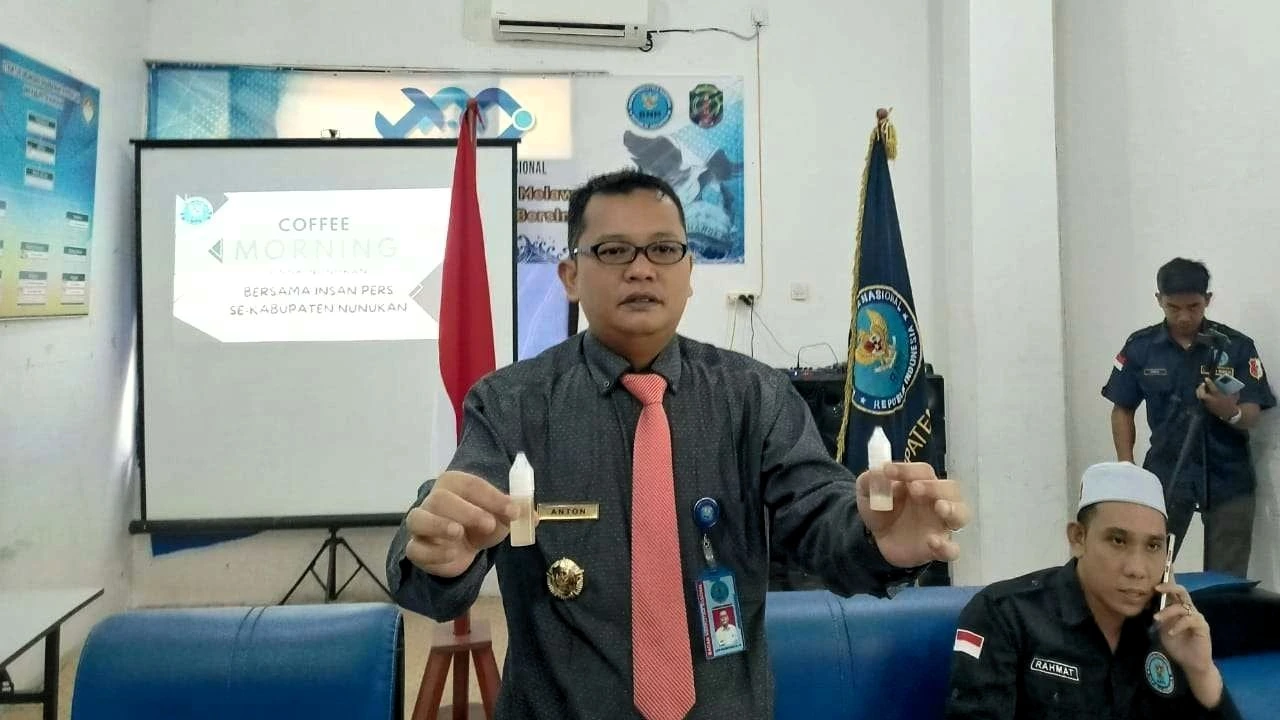Kalimantan Raya, Tarakan – Kebuntuan penyelesaian sengketa lahan antara 32 petani dengan PT Phoenix Resources International (PRI) di Tarakan menyoroti urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam Diskusi Hukum “TERAS MARJINAL” BEM Se-Kalimantan (13/11/2025), Adi Freddy Bawaeda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, membedah opsi hukum yang tersedia bagi masyarakat dan pemerintah untuk menuntut ganti rugi dan keadilan.
Menanggapi kronologis yang disampaikan perwakilan masyarakat (Yapdin) dan temuan DLH Tarakan (Endy Kurniawan) mengenai dugaan pelanggaran tahap konstruksi (dampak hidrologi), Adi Freddy menjelaskan bahwa rezim hukum lingkungan menyediakan tiga mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh, antara lain Administratif, Perdata, dan Pidana.
Freddy menegaskan bahwa fakta adanya gangguan pada produktivitas pertanian warga menunjukkan adanya kerugian yang dialami masyarakat, yang secara otomatis membuka hak mereka untuk menuntut ganti rugi.
Jika mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) seperti mediasi dan penggunaan tim appraisal (penilai) yang diusulkan oleh Pemkot Tarakan mengalami deadlock atau kegagalan, maka upaya hukum melalui Gugatan Perdata adalah koridor yang disediakan UU No. 32 Tahun 2009.
“Mahkamah Agung menguatkan putusan antara gugatan masyarakat dengan pelaku usaha. Koridor hukum itu ada dan secara normatif itu bisa dilakukan. Tidak ada yang mustahil,” tegas Adi Freddy.
Warga yang terdampak dapat mengajukan gugatan secara perorangan atau secara kelompok (Class Action). Dalam gugatan ini, kelompok masyarakat harus berhasil membuktikan adanya sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh PT PRI.
Dalam perspektif pidana, terutama untuk kasus lingkungan hidup, Adi Freddy menyoroti pentingnya prinsip pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009.
Prinsip ini berarti penggugat tidak dibebankan untuk membuktikan niat jahat (mens rea) pelaku usaha. Namun, ia juga mencatat bahwa UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) secara tidak langsung telah mereduksi penerapan prinsip ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana juga memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan Pasal 116 hingga 119 UU No. 32 Tahun 2009, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, atau bahkan pihak ketiga (subkontraktor) yang memiliki hubungan kerja (vicarious liability).
“Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, itu sangat dimungkinkan. Pengurus atau pimpinan perusahaan itu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana,” tegasnya, mencontohkan adanya kasus pidana serupa yang telah diputus di Pasuruan, Jawa Timur.
Adi Freddy juga menyinggung perubahan dalam rezim hukum lingkungan pasca UU Cipta Kerja, yang mengubah istilah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.
Ia menyebut adanya amputasi kewenangan penegakan hukum lingkungan di daerah. Dulunya, pemerintah daerah memiliki taji kuat dalam pengawasan, namun kini kewenangan cenderung tersentralisasi kembali ke pusat.
“Faktanya yang dampak yang terjadi di Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup yang ada di sini hanya dikatakan sebagai perpanjangan tangan,” kritiknya, mencermati pemaparan DLH yang harus menunggu instruksi dari KLHK.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa opsi gugatan perdata dan pidana juga terbuka bagi pemerintah (selain masyarakat dan organisasi lingkungan), di mana banyak kasus gugatan pemerintah terhadap korporasi berhasil dikabulkan oleh hakim, termasuk tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan.